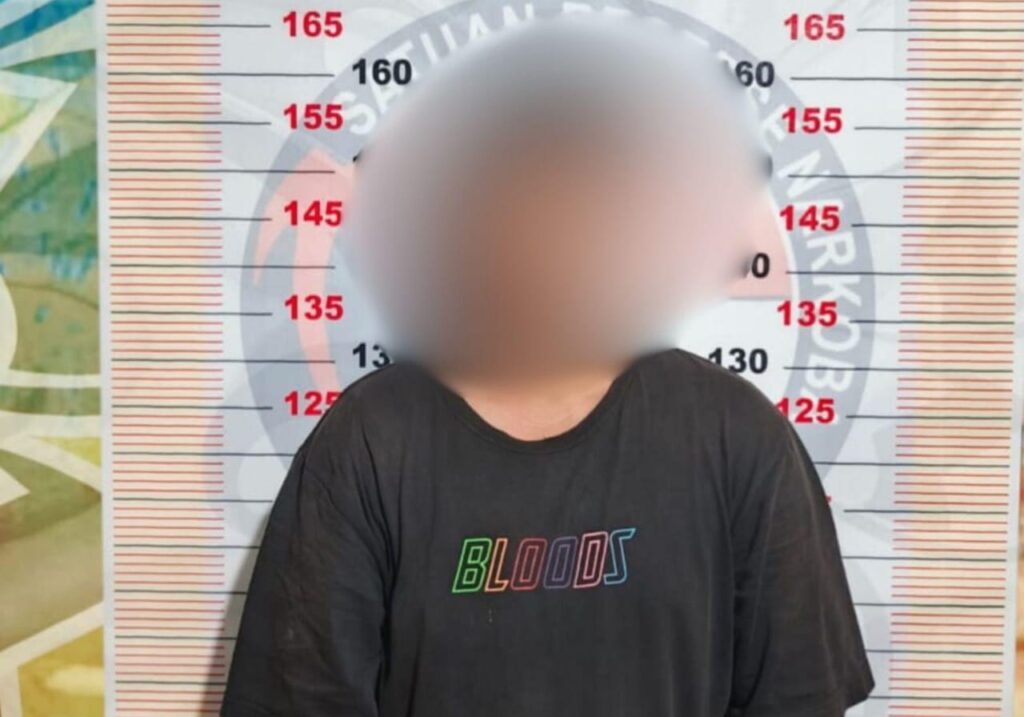HISTORIS.id – Pada dekade 1950-an, kehidupan di pelosok Sulawesi Selatan jauh dari kata tenang. Karaeng Besse, seorang gadis dari Bulukumba, merasakan langsung getirnya hidup di tengah konflik bersenjata. Seperti banyak warga di kampungnya, ia terpaksa berpindah dari satu desa ke desa lain demi mencari rasa aman. Penyebabnya: gerombolan bersenjata yang dipimpin Kahar Muzakkar.
Dari Pejuang ke Pemberontak
Kahar Muzakkar awalnya adalah seorang pejuang kemerdekaan. Namun, kekecewaannya, membuatnya angkat senjata melawan pemerintah pusat. Pemberontakannya di Sulawesi Selatan kemudian didomplengi oleh gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), sehingga publik lebih mengenalnya sebagai bagian dari DI/TII ketimbang sekadar gerombolan eks-pejuang yang kecewa.
Sejak awal 1950-an hingga awal 1960-an, kelompok Kahar Muzakkar mengganggu stabilitas keamanan di hampir seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Mereka menyebut diri “gerilyawan”, namun masyarakat menjulukinya “Gorila”—pengucapan lokal dari kata “gerilya”.
Terjepit di Antara Dua Kekuatan
Untuk menumpas Gorila, pemerintah mengerahkan TNI. Namun, situasi ini justru membuat rakyat sipil terjepit di antara dua pihak. Barbara Sillars Harvey dalam Pemberontakan Kahar Muzakkar: Dari Tradisi ke DI/TII mencatat:
– Siang hari, tentara mencurigai warga desa sebagai simpatisan Gorila.
– Malam hari, Gorila menjarah dan menuduh warga mendukung tentara pemerintah.
Perekonomian desa pun runtuh. Petani enggan menggarap sawah di tengah ancaman senjata. Windah Makkarodda dalam Karaeng Besse: Si Gadis dari Punranga mencatat, Gorila melarang warga desa pergi ke kota atau memakai barang-barang dari kota. Kedatangan pasukan pemerintah yang kadang disertai kekerasan turut membuat penduduk meninggalkan rumah dan lahan mereka.
Tragedi di Tengah Kekacauan
Besse sendiri hidup berpindah-pindah di Bulukumba dan Sinjai. Suatu ketika, kerabatnya—seorang pemain biola—ditemukan tewas dengan tubuh dicincang setelah sehari sebelumnya terlihat berbincang dengan tentara. Peristiwa itu menjadi salah satu dari banyak kisah kelam masa pemberontakan.
Meski demikian, Besse berusaha menjalani hidup. Pada November 1961, ia menikah dengan Muhammad, seorang pengelola toko di Tanete, Sinjai. Setelah pemberontakan mereda dan Kahar Muzakkar tewas pada 1965, mereka membuka Toko Muda, yang berkembang pesat hingga mampu membeli sawah dan sepeda motor.
Dari Pengungsi Menjadi Saudagar
Sejarah Bugis mencatat, meski dikenal sebagai pelaut, orang Bugis memiliki naluri dagang yang kuat. Banyak pengungsi akibat konflik justru bangkit menjadi pedagang sukses.
Di Watampone, Bone, misalnya, seorang pedagang bernama Kalla terpaksa mengungsi ke Makassar karena desanya dibakar Gorila. Pria dewasa di Bone saat itu kerap dipaksa bergabung dengan pemberontak; yang menolak dibunuh.
Di Makassar, Kalla memulai usaha dan pada 1952 mendirikan perusahaan angkutan Cahaya Bone serta NV Hadji Kalla Trading Company. Menurut Christian Pelras dalam Manusia Bugis, sejak 1955 ia sudah merambah bisnis tekstil.
Usaha itu berkembang pesat setelah keamanan Sulawesi Selatan pulih. Dari warisan inilah, putranya, Jusuf Kalla, membesarkan bisnis keluarga hingga dikenal luas di Indonesia Timur, bahkan kemudian menjadi Wakil Presiden RI di era Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo.
Pemberontakan Kahar Muzakkar bukan hanya catatan politik dan militer, tetapi juga sejarah penderitaan rakyat sipil. Dari kisah seperti Karaeng Besse dan Haji Kalla, kita belajar bahwa di balik kobaran senjata, ada daya tahan, strategi bertahan hidup, dan kebangkitan ekonomi yang lahir dari reruntuhan konflik. (*)